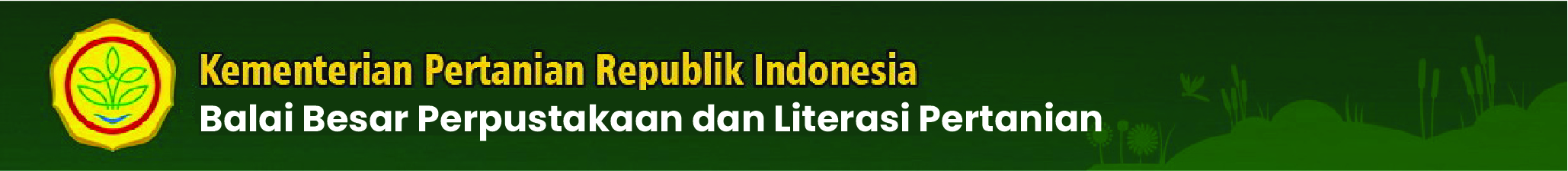Di tengah deru zaman dan kemajuan teknologi pertanian, Suku Baduy tetap setia menjaga harmoni dengan alam. Mereka tak tergoda pestisida kimia atau pupuk sintetis. Sebaliknya, suku yang tinggal di pedalaman Banten ini mewarisi ilmu pertanian dari leluhur yang penuh makna dan ramah lingkungan. Salah satu praktik paling sakral adalah Ngubaran Pare, tradisi pengobatan tanaman padi dengan ramuan alami yang dilakukan dalam ritus-ritus khusus. Tradisi ini bukan hanya soal bertani, tapi juga perwujudan doa, etika, dan filosofi hidup yang menjaga hubungan manusia, alam, dan Sang Pencipta.
Suku Baduy memiliki cara unik dalam bertani dan bertanam padi. Kegiatan pertanian dilakukan sesuai dengan aturan dan adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur. Dalam tradisi Baduy terdapat pikukuh, yaitu aturan adat khusus yang berkaitan dengan pengelolaan ladang. Pikukuh menjadi landasan hidup masyarakat Baduy dengan ajaran lojor teh meunang dipotong, pendek teu meunang disambung, gunung teh meuang dilebur, lebak teumeunang dirusak, buyut teh meunang dirobah artinya panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung, gunung tidak boleh digali, lembah tidak boleh dirusak, adat tidak boleh diubah.
Menurut aturan adat tersebut, terdapat teu wasa (pantangan) masyarakat Baduy dalam bertani, yaitu membongkar tanah dan memakai pestisida sintetis. Masyarakat Baduy menganggap sakral tanah sebagai titipan nenek moyang, pantangan menjadi batas penjaga agar daerah sakral terlindungi dari pencemaran lingkungan. Tidak digunakannya pestisida sintetis pada tanaman juga dimaksudkan supaya padi tidak tercemar racun serta dapat disimpan dalam lumbung dalam jangka waktu yang lama. Pada era modern konsep pantangan ini sejalan dengan gerakan pertanian organik (organic farming) dan biopestisida.
Aktivitas Bertanam Masyarakat Baduy
Masyarakat Baduy menggunakan huma atau ladang sebagai lahan pertanian, ladang yang dipakai adalah kebun campuran yang tidak hanya ditanami oleh padi tetapi juga tanaman lain seperti terong, cabai, talas, pisang, dan lainnya. Ngahuma atau berladang telah dianggap sebagai wujud ibadah, ritual suci dalam proses berladang adalah penghormatan masyarakat Baduy bagi Nyi Pohaci Sanghyang Asri, Dewi Padi dalam ajaran Sunda Wiwitan.
Aktivitas bertanam dilakukan berlandas pada pikukuh, pelaksanaan ritual akan dipimpin oleh Puun Cikeusik, pemimpin desa yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan keagamaan. Kegiatan dan ritual bertanam padi dilakukan dalam beberapa tahapan:
- Narawas, ritual tolak bala yang dilakukan ketika memulai pembukaan lahan.
- Nyacar, kegiatan pembabatan semak belukar untuk membersihkan lahan, dilakukan pada bulan kelima (Mei–Juni)
- Ngahuru, kegiatan membersihkan lahan dengan parang dan membakar sisa rumput serta tumbuhan, rumput kecil yang tersisa dibiarkan selama satu minggu hingga membusuk dan berfungsi sebagai pupuk. Ngahuru dilakukan pada bulan keenam (Juni–Juli).
- Menanam pangpuhunan (tumbuhan penolak bala). Tumbuhan akan berfungsi sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama dan penyakit. Kiwura, sereh, jawer, kotok, hanjuang, seueul, bingbin, bangban, koneng, panglay, pacing, dan bambu tamiang adalah beberapa tanaman yang dianggap dapat menolak bala sekaligus bermanfaat sebagai pestisida.
- Ngaseuk, kegiatan menanam padi dengan cara ditugal, jarak antar lubang tanam adalah satu telapak kaki. Setiap lubang berisi 5–7 butir benih, lubang dibiarkan tanpa ditutup tanah. Menanam padi dilakukan pada bulan ketujuh (Juli–Agustus)
- Ngubaran pare, memelihara tanaman terhadap gangguan hama dan penyakit. Ngubaran pare dapat dilakukan sebanyak 3–9 kali pada musim tanam, pelaksanaan dilakukan dalam hitungan angka ganjil.
- Ngored, kegiatan membersihkan gulma, biasanya dilakukan saat tanaman padi sudah berumur 3 bulan.
- Ngetem, memanen padi menggunakan ani-ani. Gabah dibiarkan melekat pada tangkai malai dan dibuat menjadi pocongan (ranggeong), tangkai malai diikat sebesar lingkaran ibu jari atau telunjuk. Ikatan kemudian dijemur dan disimpan dalam leuit (lumbung).
- Kawalu, ritual penyimpanan padi pada lumbung.
Ngubaran Pare dan Ramuan Penyelamat
Pengobatan padi atau Ngubaran Pare dilaksanakan dalam beberapa fase tanam, dimulai ketika padi telah mencapai umur 40 hari, upacara pengobatan padi oleh masyarakat Baduy disebut dengan Ngirab Sawan. Masyarakat Baduy menggunakan samara pangpuhunan (pestisida nabati) dalam pengobatan padi, pengaplikasian ramuan pestisida dilakukan pada fase: 1) awal pertumbuhan (40 hari setelah tanam (HST)); 2) fase anakan maksimum (60 HST); 3) fase berbunga (padi bunting); dan 4) fase pemasakan. Racikan ramuan yang dipakai dalam kegiatan dan upacara mengobati padi diantaranya:
- Samara pangpuhunan
Umur padi 40 HST: bangban, barahulu, kihura, hanjuang, bangle, pacing tawa, dan bingbin. Racikan berfungsi untuk mengusir penggerek padi, ulat, dan wereng.
Umur padi 60 HST: daun mengkudu, laos, dan jeruk bali. Racikan dipakai untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. - Tawa Kungkang
Campuran buah bingbin dan pasir sungai. Racikan ditabur ke ladang, kemudian pengobat menyemburkan air panglay. Ramuan berfungsi untuk mengendalikan wereng. - Bakaran Daun
Membakar daun beraroma menusuk yaitu walang, kanyere, dan bungur. Dilakukan untuk mengusir serangga hama. - Air kelapa
Air kelapa disembur pada tanaman, berfungsi untuk mengendalikan hama ulat. - Ramuan untuk upacara penyelamatan padi
Campuran daun mengkudu, air kelapa hijau, tuak aren, dan debu tungku dapur. Sebelum racikan ditabur ke ladang, diselenggarakan upacara terlebih dahulu untuk berdoa dan membacakan kisah kehidupan masyarakat Baduy dan kisah padi. - Ramuan upacara pascapanen
Ramuan dipakai untuk meningkatkan daya simpan padi dan memelihara biji dari gangguan serangga. Terdapat beberapa upacara yang dilakukan setelah padi dipanen, seperti:
- Ngadieukeun pare, upacara menyimpan padi setelah panen. Ramuan terdiri dari gharu, akar jambaka, kulit buah pisitan, tempurung kelapa, dan abu dapur. Racikan kemudian dibakar dibawah lumbung padi.
- Ngepret, upacara memelihara atau menjaga padi yang telah disimpan dalam lumbung. Padi diciprati ramuan yang terdiri dari jaringau, cikur, panglay dan air.
- Ngocek, upacara pengambilan padi dari lumbung. Ramuan terdiri dari daun sirih, jambe atau pinang, kapur, dan gambir.
Perubahan zaman dan globalisasi tidak membuat masyarakat Baduy melupakan warisan ilmu pertanian nenek moyangnya. Keteguhan dan konsistensi memelihara lingkungan adalah bentuk kepedulian manusia terhadap lestarinya ekosistem sekaligus praktik nyata perwujudan pertanian berkelanjutan.
Sumber:
- Dinata, Arda. "Ngubaran Pare dengan Biopestisida." Inside, Jun. 2011. https://www.neliti.com/publications/243638/ngubaran-pare-dengan-biopestisida#cite
- Kurniawati, S., Setyowati, I., & Saryoko, A. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy dalam Mengendalikan Hama dan Penyakit Padi. Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/7210